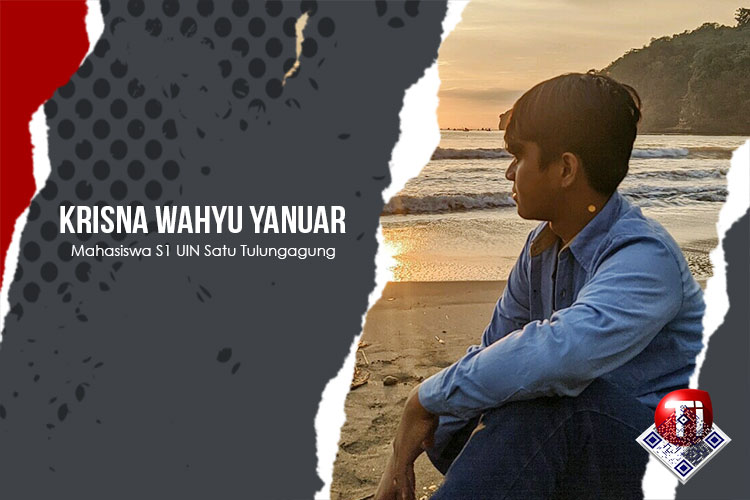
TIMESINDONESIA, TULUNGAGUNG – Jagat dunia maya adalah jagat baru setelah dunia yang asli. Tetapi terkadang memiliki bias-bias yang bisa membuat guncangan yang tidak bisa dikontrol.
Salah satu fenomena media sosial adalah terminologi "viral", yang mau tidak mau masyarakat konsumsi sebagai komoditas publik. Antusias dari masyarakat media sosial atau netizen, membuat suatu hal yang unik yakni "Interconnection" atau keterhubungan.
Advertisement
Masyarakat pada hari ini menjalani dua kehidupan ganda sekaligus. Maka dari itu permasalahan-permasalahan maya maupun asli ia turut berkabung atas pengalamanya itu. Tetapi persoalannya adalah reaksi dari dunia maya itu, yang tidak bisa dikontrol.
Munculnya "Cyber War", sebenarnya sudah disadari seluruh masyarakat, tetapi mereka terkadang lupa akan status asli mereka di dunia media sosial yang terkadang ada sangkut pautnya kejadian asli.
Cyber Bullying adalah salah satu perang siber yang sering terjadi. Menurut Times Indonesia.co.id, perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab maraknya cyberbullying. Unicef merilis data pada tahun 2022, sebanyak 45% dari 2.777 responden anak Indonesia mengaku telah menjadi korban cyberbullying. Ditambah lagi dengan temuan Microsoft, bahwa Indonesia memiliki tingkat kesopanan terendah di dunia maya.
Akibat daripada itu komentar- komentar negatif tidak bisa dicegah, trend- trend satire yang berujung bullying dalam media sosial, sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Yang ditakutkan adalah kematian dari status subjek yang di bullying.
Juga bisa jadi berakibat Deep Traumatic (trauma yang mendalam), atau yang paling parah adalah timbulnya Chaos (perubahan sosial) yang mendadak akibat penggiringan opini yang merujuk kepada bullying kelompok, yang juga bisa berakibat fatal dalam dunia nyata.
Hal- hal seperti itu dianggap sebagai kekerasan simbolik. Melalui buku-buku yang ditulis secara sistematis disebut Reproduksi dalam Pendidikan, Masyarakat dan Budaya 1970, Bourdieu mendefinisikan kekerasan bentuk simbolik memaksakan sistem simbolisme dan struktur (misalnya budaya) pada kelompok atau kelas tertentu sedemikian rupa sehingga dianggap melegitimasi sesuatu.
Bourdieu melihat kekerasan simbolik sebagai akibat utama dari penggunaan bahasa dan simbol. Dia mengerti bahwa bahasa dan simbol adalah satu cara efektif untuk menciptakan orang- orang saling mendominasi. Ini mereka melakukannya dengan cara yang berbeda, tetapi dengan satu cara Bourdieu menekankan kontrol yang dilakukan untuk menetapkan kesalahan.
Dalam kondisi tersebut, Bourdieu mengatakan bahwa bahasa bukan lagi sistem proposisi, hukum, dan penalaran teoretis, tetapi bahasa telah menjadi bagian integral dari perjuangan untuk mendominasi orang lain.
Pada hari ini kekerasan simbolik disadari atau tidak sudah banyak beredar di media sosial, mulai dari berita yang memberikan kesan majas hiperbola, sesuatu yang dilebih- lebihkan seolah- olah dramatis, melupakan sisi humanis, dengan terus mengejar rating oriented dan money oriented.
Kekerasan simbolik terjadi pada struktur berita yang dilebih- lebih menggiring opini kesana kemari. Kemudian komentar-komentar yang mengundang abstraksi atau memunculkan tafsir yang beragam, yang mana ada beberapa kelompok yang mengalami diskriminasi atas komentar- komentar itu.
Negara pun tidak bisa menjamin untuk mengontrol hal tersebut, karena adanya pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adanya pasal itu tidak menjamin menjadi pasal karet untuk membungkam kritik, atau menyerang satu sama lain.
Ada juga dengan content- content video yang beredar yang menyimbolkan hal- hal patriarkis, yang merendahkan martabat wanita, juga ada satire- satire yang melebihi batas, atau tidak mengerti batas, atau bahkan batas apa yang ada dalam media sosial itu pun masih problematik.
Selama ini manusia sebagai pengguna media sosial harus berefleksi tujuan media sosial dibuat. Bijak digital, literasi digital, narasi yang sudah usang, semua kembali kepada self control dirinya sendiri, dan etika diri sendiri.
Semua kembali lagi pada bagaimana moral manusia itu bekerja dalam dunia kedua, yakni media sosial?, Tapi pada akhirnya lagi kejenuhan itu akan mengantarkan manusia kepada teologi diri sendiri dan teologi sosial. Atau menganggap media sosial sebagai hiburan tidak mengapa, kembali kepada diri sendiri bagaimana ketika nurani sudah berbicara, atas hal- hal yang terjadi kini.
Pada akhirnya manusia akan menjelajahi bagaimana media sosial dan platform untuk menguntungkan dirinya, memberikan dampak apa pada dirinya, disertai itu, penjelajahan akan produk manusia itu juga harus disertai keyakinan diri akan pengetahuan. Dimana juga menggerakkan religiusitas manusia akan media sosial.
Kecenderungan manusia kembali pada Teologi murni, karena manusia sendiri juga sendiri pada hari ini juga mengalami Ambivalensi terhadap kekerasan simbolik yang sulit dicegah.
Narasi-narasi positif dan konstruktif sulit membendung narasi-narasi ganas dan kapitalisme digital yang brutal, identitas manusia diperjual belikan. Kematian diri sendiri dalam judul diatas adalah, kebingungan kita akan hal yang sudah masif dan liar, manusia dijadikan ajang adu domba, dan arena bertempur oleh platform- platform baru atau yang terkenal.
Konsumsi akan hal tersebut harus disadari sebagai proses masyarakat menghasilkan interaksi. Tetapi spiritualitas yang seharusnya dijadikan landasan utama untuk mengarungi hal-hak tersebut.
Mungkin sedikit naif, tetapi beginilah adanya, Digital Pressure (Tekanan Digital) harus diberikan nutrisi untuk mengimbangi hal- hal tersebut dengan produktivitas diri dan efikasi diri (Kemampuan diri sendiri). Semuanya kembali lagi kepada kita sebagai subjek utama. Sekian, semoga bermanfaat.
***
*) Oleh: Krisna Wahyu Yanuar, Mahasiswa S1 UIN Satu Tulungagung.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |

