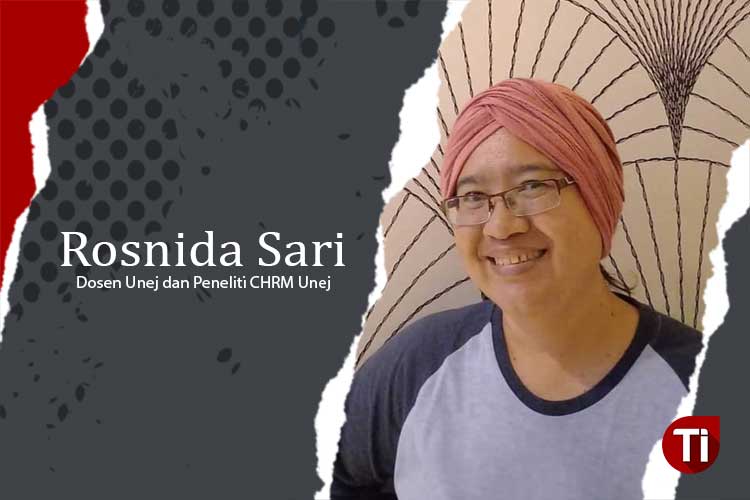
TIMESINDONESIA, JEMBER – Bagi sebagian orang istilah anak budaya ketiga atau individu budaya ketiga merupakan istilah yang masih terdengar baru. Mereka ini biasanya anak-anak dari orang tua yang berkewarganegaraan berbeda atau anak yang sering dibawa berpindah-pindah negara. Ini dialami oleh anak yang lahir dan besar di luar negeri seperti mereka yang orang tuanya pegawai kementrian luar negeri, militer, bisnisman, mereka yang orang tuanya berpindah-pindah karena bekerja sebagai pelayan gereja atau bahkan anak dari pernikahan beda negara.
Ruth Hill Useem memperkenalkan istilah ini pertama kali pada tahun 1960-an ketika ia melakukan pekerjaan antropologi di wilayah India. Istilah ini kemudian di definisikan kembali oleh David Pollock “anak budaya ketiga merupakan individu yang menghabiskan sebagian besar tahun-tahun perkembangan budayanya diluar dari budaya orang tuanya. Semua element dari budaya-budaya itu mereka gabungkan menjadi pengalaman hidup mereka. Rasa memiliki satu sama lain lebih mereka prioritaskan pada mereka yang memiliki pengalaman atau budaya yang serupa”.
Advertisement
Anak-anak ini kemudian memiliki 3 budaya yaitu: Pertama, budaya dari negara asal. Kedua, budaya dari berbagai tempat dimana mereka tinggal. ketiga, budaya yang mereka hasilkan sendiri hasil dari kontemplasi dari berbagai pengalaman tinggal di negara asing sebelumnya.
Saya menemukan hal ini menjadi sesuatu yang menarik. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan teman Amerika yang 15 tahun tinggal di Aceh. Namun saat ini mereka harus pindah ke salah satu wilayah di Jawa Tengah yang berbeda sekali geografisnya. Jika di Aceh mereka tinggal di wilayah pantai, di Jawa Tengah mereka tinggal di wilayah pegunungan. Ketika orang-orang bertanya mereka berasal dari mana salah seorang anak berkata bahwa ia berasal dari Aceh. Ibunya, lalu menunjukkan passport Amerika yang mereka miliki, namun si anak tetap merasa bahwa dirinya berasal dari Aceh. Ini bisa dipahami karena ia hanya lahir di Amerika namun besar di Aceh, sehingga sepanjang apa yang diingatnya adalah semua pengalaman ketika berada di Aceh.
Anak-anak yang dikenal dengan sebutan anak budaya ketiga atau juga dikenal dengan sebutan global nomad ini memiliki sisi positif dan negatif. Saya mencoba bertanya pada beberapa teman yang memiliki anak yang masuk kategori ini. Pertama teman yang berasal dari US namun menetap di Indonesia, kedua teman yang menikah beda negara dan ketiga teman yang menjadi ASN dan ditugaskan ke beberapa negara. Bagi mereka ada hal-hal positif yang di dapat dari pertemuan budaya-budaya berbeda itu.
Dari hal positif
Pertama, anak jadi belajar untuk mudah beradaptasi. Anak yang berpindah-pindah ini tentu membutuhkan waktu yang singkat agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini membuat si anak belajar bagaimana beradaptasi lebih cepat dibandingkan anak yang baru pertama sekali berpindah, misalnya mahasiswa yang harus pindah dari kotanya ke kota dimana ia menuntut ilmu.
Kedua, mencari teman baru. Anak budaya ketiga menjadi anak yang mudah untuk mencari teman baru. Ini juga dikarenakan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat.
Ketiga, lebih bisa menerima perubahan. Karena kebiasaan berpindah-pindah membuat mereka menjadi lebih cepat menerima perubahan.
Keempat, fleksibel, dinamis dan terbuka karena sering berpindah, ditempa lingkungan yang berbeda-beda.
Kelima, resilient atau tangguh, karena sering berpindah-pindah mereka menjadi orang yang tangguh dan teguh menghadapi tantangan
Keenam, mendukung pluralisme dan menghormati perbedaan tanpa menghakimi atau ketakutan. Karena sering berinteraksi dengan budaya yang berbeda, mereka menjadi anak yang mendukung keberagaman dan tidak mudah untuk menghakimi mereka yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan malah bahkan berbeda orientasi seksual.
Salah seorang teman yang sempat saya ajak mengobrol mengatakan bahwa budaya yang baru bisa memberikan anak-anak mereka pengetahuan yang lebih antar budaya. Tidak serta-merta "terpengaruh" budaya baru, tapi jadi mengerti bahwa ada kebiasaan lain di luar budaya Indonesia. Ini membuat anak-anak itu menjadi lebih bijaksana.
Kata teman ini “contohnya di beberapa negara di mana kami pernah tinggal, memberi atau menerima dengan tangan kiri tidak masalah. Namun di Indonesia itu masalah, karena terkait dengan tata-krama kesopanan. Saya dan anak-anak berdiskusi, kalau lagi di luar Indonesia bahkan dalam rumah, saya tidak masalah mereka memberi atau menerima dengan tangan kiri (salah satu anak saya left-handed). Namun, kalau di Indonesia, gunakanlah tangan kanan, bukan karena tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri (sebab sama-sama ciptaan Tuhan) tapi karena masalah kebiasaan tata-krama saja. Anak-anak saya jadi bisa belajar lebih bijak dalam menghadapi tata-laku bangsa-bangsa, tidak kaku”.
Namun begitu ada hal negative juga yang dihadapi oleh anak-anak budaya ketiga ini:
Pertama, kurang tahu sejarah atau akar budaya asli orang tuanya (karena besar atau tinggal di negara lain). Ini dialami oleh salah seorang teman yang saya ajak ngobrol. Ia berusaha mengenalkan budaya Indonesia pada anaknya dengan cara membawa anak ke tempat-tempat bersejarah di beberapa tempat di Indonesia.
Kedua, bisa merasa tidak stabil karena sering berpindah-pindah lokasi. Kebiasaan yang terus berpindah-pindah tentunya membuat anak menjadi labil. Mereka gamang dengan identitas mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan napa yang dikatakan oleh David Pollock diatas bahwa “anak budaya ketiga akan berasimilasi dengan semua budaya yang dia miliki sehingga susah baginya mengidentifikasi ia berasal dari budaya yang mana”.
Ketiga, kesulitan beradaptasi yang pada akhirnya menarik diri dari pergaulan. Ini dialami oleh teman yang berasal dari US. Ketika pindah ke Jawa Tengah, salah seorang anak mereka menjadi stress, sehingga tidak bisa berkonsentrasi untuk sekolah. Ini menyebabkan ayah dan ibunya menyisakan sedikit waktu di sekolah. Selebihnya mereka mengajar anak mereka di rumah sampai situasinya memungkinkan untuk bisa masuk full time.
Keempat, tidak mempunyai teman baik yang awet lama. Karena seringnya berpindah-pindah, anak-anak ini sedikit yang memiliki teman yang bisa bertahan lama.
Kelima, membentengi diri karena tidak mau sakit hati ditinggal teman lagi. Kehidupan nomad yang mereka alami membuat mereka enggan untuk mau membangun lagi pertemanan yang baru, karena sudah tertanam di pikiran bahwa mereka akan pindah lagi sehingga sia-sia saja membangun pertemanan baru ditempat baru.
Keenam, menolak menerima perubahan. Bagi anak-anak yang sudah lelah berpindah-pindah, menolak menerima perubahan lazim terjadi. Ini karena mereka harus belajar kembali hal-hal baru dari budaya baru yang mereka masuki. Situasi ini biasanya terjadi kalau mereka pindah setelah usia remaja.
Meski memang terdapat beberapa hal negatif, namun kita membutuhkan anak-anak budaya ketiga yang lebih banyak. Ini karena banyak hal positif yang telah tertanam di diri mereka, terbentuk sepanjang perjalanan ke berbagai negara. Misalnya saja, sikap toleran dan anti diskriminasi. Hal seperti ini masih sedikit bisa dipahami oleh orang awam. Oleh karena itu, sepertinya banyak hal dimana kita bisa belajar pada anak dari budaya ketiga. (*)
*) Oleh : Rosnida Sari, Ph.D., Dosen Unej dan Peneliti CHRM Unej.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |

