Potensi Tsunami 29 Meter, Pantai Selatan Jatim Belum Terpasang Buoy

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pantai Selatan Jawa Timur berpotensi diterpa gelombang tsunami setinggi mencapai 29 meter. Demikian ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat Webinar Kajian dan Mitigasi Gempa dan Tsunami di Jawa Timur pada 28 Mei 2021 kemarin.
BMKG sendiri telah menyiapkan beberapa skenario dengan kemungkinan magnitudo gempa tertinggi 8,7 M. Ukuran tersebut menjadi dasar untuk memprediksi terjadinya tsunami sekaligus sebagai dasar pemetaan bahaya.
Advertisement
Bahkan ada wilayah yang tercatat berpotensi tsunami dengan gelombang tertinggi yaitu Trenggalek. Dengan tinggi maksimum mencapai 26-29 meter. Sedangkan Blitar berpotensi mengalami tsunami dengan waktu paling cepat.
Namun saat ini peralatan deteksi tsunami di Jatim hanya mengandalkan Tide Gauge untuk mendeteksi gelombang tsunami ketika sudah mendekati bibir pantai.
"Kelemahannya memang peralatan kita terbatas," terang Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan, Suwarto, S.Si, kepada TIMES Indonesia, Kamis (3/2/2021).
Tide Gauge saat ini terpasang di pantai Pacitan, Tulungagung, dan Muncar Banyuwangi. Peralatan tersebut masih beroperasi sampai sekarang guna memantau tinggi gelombang laut.
Namun, jelasnya, ada peralatan detektor tsunami lebih canggih dengan hasil deteksi lebih cepat karena terpasang di tengah laut. Peralatan ini berbasis buoy atau yang dikenal dengan InaBuoy. Piranti ini masuk dalam kategori Tsunami Early Warning System (TEWS) buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Pada awalnya, Buoy dipasang untuk aktivitas bongkar muat kapal laut. Namun, alat ini kemudian difungsikan untuk mengamati terjadinya gelombang pasang dan tsunami yang mungkin terjadi di kawasan tersebut.
Awalnya pendeteksian dilakukan oleh alat yang diberi nama Ocean Bottom Unit atau OBU yang diletakkan di dasar laut. OBU akan secara langsung mengirim data melalui underwater acoustic modem ke buoy tsunami yang terpasang di permukaan laut.
 Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan, Suwarto, S.Si.(FOTO: Dok. TIMES Indonesia)
Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan, Suwarto, S.Si.(FOTO: Dok. TIMES Indonesia)
Kemudian, Buoy tsunami mengirim data tersebut via satelit ke pusat pemantau tsunami Read Down Station (RDS), di Indonesia terdapat di Gedung I BPPT lantai 20. Sehingga tsunami terdeteksi lebih dini dan memberikan cukup waktu untuk evakuasi.
"Dulu sempat ada Buoy yang di tengah lautan, namun posisinya rusak tidak beroperasi sampai sekarang belum ada lagi," jelas Suwarto.
Akan tetapi, Suwarto menambahkan, alat tersebut memang belum terpasang di laut selatan Jatim.
"Kayaknya memang belum ada, kemarin waktu habis tsunami Aceh banyak yang dipasang di Sumatra. Oh, selatan Bali kalau nggak salah pernah ada," tandasnya.
Suwarto mengatakan, perawatan buoy memang membutuhkan anggaran cukup besar hingga miliaran rupiah.
"Pengadaannya mahal, pemeliharaannya juga mahal," tambahnya.
"Jadi kan ya otomatis dari segi dana itu yang jadi kendala. Mungkin pemerintah juga belum memperhatikan di situ, mungkin masih kalah dengan yang lain. Anggarannya untuk yang lain, kelemahannya di situ," tandas Suwarto.
Lebih lanjut, Suwarto mengatakan, potensi tsunami merupakan hasil kajian para ahli berupa potensi gempa di selatan Jawa.
"Tetapi itu adalah hasil kajian atau penelitian, bukan prediksi. Jadi tidak perlu sampai panik," terangnya.
Namun ia mengimbau bagi warga yang berada di pantai selatan mulai dari Banyuwangi, Jember, Lumajang, Tulungangung, Blitar sampai Pacitan mengantisipasi potensi terjadinya tsunami.
Terutama daerah-daerah yang menghadap pantai agar memetakan jalur evakuasi. Sehingga ketika nanti terjadi gempa besar, tidak perlu menunggu info dari BMKG. Warga bisa langsung ambil tindakan mengevakuasi diri. Termasuk membudayakan mitigasi bencana berbasis masyarakat.
"Kalau gempanya dirasa cukup besar daerah-daerah yang dekat pantai atau mungkin pas di pantai segera menjauh dari pantai. Kita biasakan atau membudayakan ketika ada gempa besar menjauh dari pantai, tidak perlu menunggu info dari BMKG. Walaupun dari BMKG sendiri itu mesti ada info nanti, apakah gempa itu berpotensi tsunami atau tidak," jelasnya.
Kepada masyarakat yang ada di pesisir khususnya dan masyarakat yang ada di daerah Jatim, Suwarto menjelaskan bahwa saat ini kita memang tinggal di daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Di sepanjang selatan Jatim merupakan zona subduksi atau tumbukan lempeng yang merupakan sumber gempa bumi dan suatu saat bisa terjadi.
Di samping itu juga ada sumber-sumber gempa yang lain seperti Sesar Waru, Sesar Surabaya dan Sesar Grindulu Pacitan.
Gempa memang tidak bisa diprediksi juga tidak bisa dicegah, maka yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan mitigasi atau persiapan. Antara lain membuat bangunan yang tahan terhadap gempa bumi sesuai standar PU. Kemudian mengantisipasi dengan pemahaman terhadap gempa bumi dan tsunami.
"Jadi ketika ada gempa, apa yang harus kita lakukan. Kita evakuasi ke mana, jalur evakuasi di mana, kemudian kita mengetahui daerah-daerah mana yang rawan. Kita mengetahui seluk beluk jalur-jalur evakuasi," bebernya.
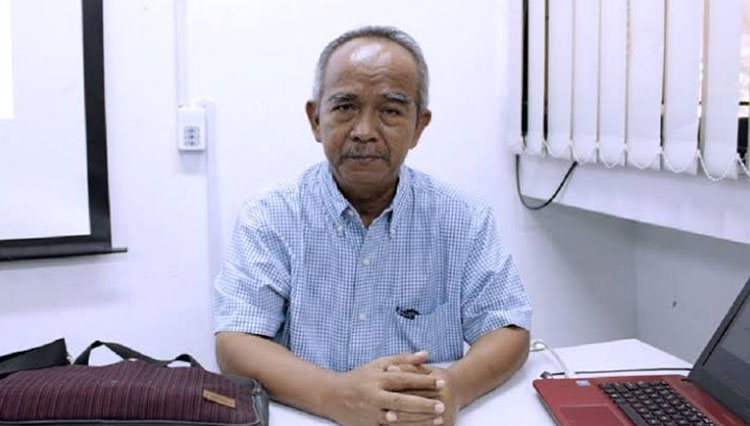 Pakar Geologi ITS Dr Ir Amien Widodo.(FOTO: Dok. TIMES Indonesia)
Pakar Geologi ITS Dr Ir Amien Widodo.(FOTO: Dok. TIMES Indonesia)
Sementara itu, Pakar Geologi ITS Dr Ir Amien Widodo menilai, peralatan detektor tsunami juga harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat akan bencana. Tide Gauge bahkan cukup membantu peringatan dini asal warga paham mitigasi.
"Tide Gauge cukup, tapi masyarakatnya juga harus disiapkan," jelas Amien.
Sistem Peringatan Dini (SPD), lanjutnya, bukan alat utama dalam menghadapi ancaman sebab alat tersebut mempunyai keterbatasan, bisa ngadat/rusak atau hilang.
"Namun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi gempa bumi dan tsunami bukan sekadar masalah teknologi melainkan juga masalah sosial budaya dan ekonomi politik yang perlu dilatihkan secara kontinyu agar bisa menjadi budaya keselamatan," tambahnya.
Dia mencontohkan, seperti upaya yang dikembangkan masyarakat Pulau Simelue yang selamat dari tsunami tanggal 26 Desember 2004.
Masyarakat Pulau Simelue belajar dari kejadian bencana tsunami yang terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu (tahun 1900) dan mengembangkan sistem peringatan dini dengan teriakan #SMONG yang berarti air laut surut dan segera lari menuju kebukit.
Istilah ini selalu disosialisasikan dengan cara menjadi dongeng legenda oleh tokoh masyarakat setempat sehingga istilah ini melekat dan membudaya di hati setiap penduduk P Simelue.
"Istilah ini yang menyelamatkan hampir seluruh rakyat Pulau Simelue padahal secara geografis letaknya sangat dekat dengan pusat tsunami 2004," imbuh Amien.
Masyarakat yang berasal dari P Simelue dan bekerja di sepanjang pantai barat Sumatra menjadi pahlawan karena menyelamatkan banyak orang dengan menyuruh dan memaksa orang segera berlari secepatnya menuju tempat yang tinggi begitu melihat air laut surut.
"Mengingat kawasan pantai selatan sudah sering diterjang tsunami, mestinya mereka sudah mengembangkan sistem peringatan dini," jelasnya.
Kecerdasan Lokal
Amien menjelaskan, secara geologis, posisi Indonesia terletak di kawasan tektonik aktif karena ditekan oleh tiga lempeng aktif.
Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Samudera Indo-Australia bergerak ke utara dan menghujam ke bawah lempeng Benua Euro-Asia.
Lempeng Pasifik bergerak ke barat menghujam di bawah lempeng Benua Eurasia. Tumbukan antar lempeng ini dikenal dengan istilah subdukasi dan menghasilkan gempa subduksi dengan kedalaman dangkal sampai dalam.
Gempa subduksi dangkal sering disebut gempa Megathrust dengan magnitudo besar dan bisa diikuti tsunami. Pada umumnya tsunami bisa terjadi jika gempanya berkekuatan lebih dari 6,5 SR, pusat gempa berada di laut pada kedalaman kurang dari 70 km, dan terjadi deformasi vertikal.
"Akibatnya, kawasan-kawasan yang terletak di dekat zona tumbukan (subduksi) akan berpotensi terkena tsunami," katanya menambahkan.
Kawasan tersebut meliputi Pantai Barat Sumatra, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi serta Pantai Utara Papua.
"Proses tumbukan tumbukan lempeng ini sudah berlangsung sebelum manusia diturunkan ke bumi, ini berarti gempa dan tsunami sudah terjadi berulang-ulang," jelas Amien.
Sejarah mencatat, sejak awal abad ke-20, Pantai Selatan Jawa telah dilanda oleh 20 kali kejadian tsunami yang dipicu oleh guncangan gempa bumi.
Wilayah yang pernah dilanda tsunami tersebut antara lain Pangandaran (1921, 2006), Kebumen (1904), Purworejo (1957), Bantul (1840), Tulungagung (1859), Jember (1921) dan Banyuwangi (1818, 1925, 1994).
Umumnya masyarakat yang bermukim di kawasan pantai telah mengetahui dan memahami potensi-potensi bencana di daerahnya, dan merekapun sudah membentuk kearifan lokal dalam menyikapi semua bencana.
"Mereka belajar sambil bekerja (learning by doing)," tandasnya.
Saat ilmu pengetahuan masih terbatas, bila ada masalah atau peristiwa alam yang luar biasa di luar jangkauan pikiran mereka saat itu maka selalu dikaitkan dengan makhluk halus yang ada di sekitarnya.
"Istilahnya yang nunggu (mbaurekso) marah. Saat terjadi gelombang besar menghancurkan dan membunuh mereka maka mereka mengatakan penunggu laut selatan sedang marah," tutur Amien.
Hal itu, kata Amien, sama halnya saat orang barat menyikapi peristiwa di luar nalar mereka. Misalnya sampai sekarang orang masih belum bisa menerangkan bagaimana membangun piramida. Orang barat menyebut ada campur tangan makhluk luar angkasa (UFO).
"Jadi senada, kita menganggap ada mahluk halus, sementara orang barat menyebut UFO," ujarnya.
Lantas sistem seperti apa yang dikembangkan untuk menyikapi kejadian ombak besar (tsunami) tersebut?
"Kita bisa belajar dari masyarakat sekarang, dimana mereka selalu memberi sesaji di tempat kejadian pada hari kejadian dan lokasi kejadian misalnya saat terjadi kecelakaan di pinggir jalan," jelasnya lagi.
Para leluhur melakukan upacara untuk meredam kemarahan penguasa pantai selatan dan untuk mengenang hari ini di lokasi. Mereka melakukan upacara sesaji bersama-sama yang dikenal dengan labuhan.
"Jadi, labuhan itu merupakan upaya leluhur untuk mengingatkan anak cucu tentang peristiwa tsunami yang terjadi pada hari dan jam saat labuhan tersebut," ujarnya.
Amien mecontohkan, upacara Palu Nomoni yang diselenggarakan tanggal 28-30 September 2018, merupakan salah satu contoh bagaimana rakyat Palu melakukan semacam sedekah laut pada waktu yang sama saat tsunami menerjang Palu 28 September 2018 sore. Sehingga kecerdasan lokal ini bisa dijadikan modal sosial masyarakat pantai selatan dalam menghadapi tsunami di masa depan mereka. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Imadudin Muhammad |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |

