Darurat Polusi dan Kemacetan, Saatnya Kebijakan Beralih ke Transportasi Publik Digalakkan
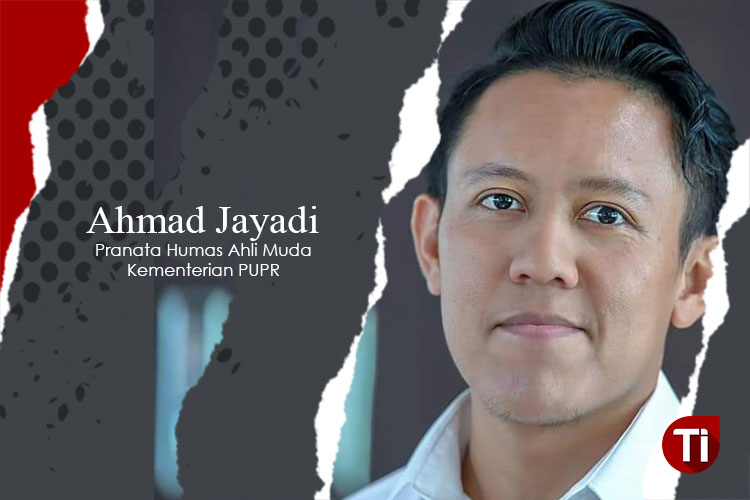
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Belakangan ini ramai diberitakan mengenai kemacetan dan tingkat polusi udara di kawasan Jabodetabek, khususnya Jakarta yang semakin memburuk. Mengutip paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Senin (14/8/2023) lalu pada Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara terkait kualitas udara Jabodetabek yang memburuk, disebutkan sektor transportasi merupakan pengguna bahan bakar paling besar di Jakarta.
Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida (CO) terbesar, disebutkan disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% atau 28.317 ton per tahun, disusul pembangkit listrik 1,76% 5.252 ton per tahun dan industri 1,25% mencapai 3.738 ton per tahun. Sepeda motor merupakan menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibanding mobil pribadi bensin, mobil pribadi solar, mobil penumpang, dan bus. Dengan populasi mencapai 78% dari total kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebanyak 24,5 juta kendaraan, dengan pertumbuhan 1.046.837 sepeda motor per tahun.
Advertisement
Data tersebut serupa dengan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta 2020 dimana sektor pembangkit listrik, termasuk PLTU, hanya memiliki pengaruh sebesar 5,7 persen (peringkat ketiga) terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta. Sumber emisi transportasi masih menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara di Jakarta.
Jika melihat kondisi tersebut, sudah sepatutnya kebijakan peralihan ke transportasi publik mulai digalakkan, karena solusi perbaikan kualitas udara di Jabodetabek sejalan dengan solusi mengurai kemacetan. Memang, mobilitas yang tinggi di perkotaan menuntut tersedianya sarana transportasi umum yang andal. Kembali mengutip pernyataan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego yang sangat menyentil, “Bahwa Negara maju bukan tempat di mana orang miskin memiliki mobil. Negara maju adalah tempat orang kaya menggunakan transportasi umum.”
Persoalan transportasi berkaitan erat dengan pembangunan kota keberlanjutan yang berwawasan lingkungan. Mengutip tulisan Kenworthy, Jeffrey R (2006) dalam bukunya yang berjudul The eco-City: Ten Key Transport and Planning Dimensions for Sustainable City Development, dikatakan bahwa transportasi yang baik merupakan jantung dari kota keberlanjutan hingga ke tingkat global.
Indonesia Traffic Watch (ITW) dalam pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu menilai, permasalahan polusi udara akibat lalu lintas dan angkutan jalan yang sekarang mencuat adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang selama ini dilakukan. Ketua Presidium ITW Edison Siahaan menuturkan, kendati sudah sejak lama diingatkan agar melakukan pembatasan jumlah kendaraan, namun kebijakan itu tak kunjung dilakukan.
Berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah saat ini pun masih dinilai tidak serius untuk menangani kemacetan sekaligus mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Sejauh ini kebijakan penanganan kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang hebat dan bahkan sudah dibahas di tingkat kabinet, namun solusinya hanya Work From Home (WFH) dan pembatasan gerak kendaraan yang masih sebatas skema ganjil genap.
Sebetulnya jika menilik semua akar masalah kemacetan terjadi karena jumlah populasi dan jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta dan Bodetabek sudah melebihi kapasitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sudah mencapai 21,75 juta unit, atau tumbuh 7,6 persen dengan proporsi tertinggi adalah sepeda motor mencapai 75,92 persen. Sebaliknya pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen/tahun dan diperparah dengan kondisi jalan yang rusak serta penutupan sebagian jalan karena proyek abadi gali tutup lubang utilitas bawah tanah.
Jika memang mau mencari akar masalah kemacetan, maka dibutuhkan ketegasan regulasi yang mendukung penggunaan angkutan umum, serta mengeluarkan regulasi untuk mengurangi jumlah populasi kendaraan pribadi dan memperbaiki transportasi umum di Jakarta.
Pembangunan transportasi massal di kota-kota besar di Indonesia saat ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sistem transportasi di ibu kota Jakarta sebagai cerminan bangsa Indonesia pun masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura yang telah membangun Mass Rapid Transportation (MRT) sejak 1987 dan menjadi sistem transportasi tertua kedua di Asia Tenggara setelah sistem transportasi LRT di Filipina.
Sistem transportasi di ibu kota Jakarta sebagai cerminan bangsa Indonesia pun masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura yang telah membangun Mass Rapid Transportation (MRT) sejak 1987 dan menjadi sistem transportasi tertua kedua di Asia Tenggara setelah sistem transportasi LRT di Filipina. Indonesia bisa dibilang sangat terlambat dalam pengembangan tranportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, menyusul beroperasinya TransJakarta yakni sebuah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pada tahun 2004.
Meskipun terlambat, namun Jakarta terus berbenah dengan dimulainya pembangunan MRT dengan rute pertamanya dari Bundaran HI-Lebak Bulus sepanjang 15,7 kilometer dan mulai beroperasi sejak Maret 2019 lalu. Pembangunan MRT sebagai transportasi publik di tengah perkotaan Jakarta selain kereta bisa dibilang sudah sangat jauh terlambat dengan Singapura.
Padahal ide jalur kereta bawah tanah sudah muncul sejak masa Presiden Soekarno. Hal tersebut dapat dilihat dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 76 tahun 1964 tentang perubahan dan pemindahan lintas-lintas kereta api pengangkut barang dan penumpang dengan tujuan ke dan dari Jakarta Raya dan Keppres RI Nomor 77 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Perubahan dan Pemindahan Lalu Lintas Kereta Api serta Pembangunan Jalur Kereta Bawah Tanah. Seandainya ide tersebut terealisasi sejak 50 tahun silam, mungkin transportasi publik Jakarta tidak akan kalah dari negara tetangga dan kemacetan bisa tidak separah saat ini.
Masyarakat sudah terlanjur dimanjakan puluhan tahun dengan kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin dipermudah dengan adanya sistem pembelian kredit alias mengutang. Untuk itu perlu adanya push policy (kebijakan yang mendorong masyarakat beralih ke kendaraan umum). Di antaranya yang telah dimulai dengan kebijakan ganjil genap, rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), atau jika dimungkinkan pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, dan berbagai kebijakan lainnya.
Berdasarkan data BPS, dalam 5 tahun terakhir, cakupan pelayanan transportasi publik di Jakarta sudah meningkat hampir dua kali lipat dari 42 persen menjadi 82 persen. Hal ini tentu merupakan data yang baik yang harus disambut dengan kebijakan yang mendorong warga menggunakan transportasi umum.
Keterkaitan antara transportasi umum atau integrasi antarmoda harus menjadi perhatian. Sebab mengutip halaman bptj.dephub.go.id, salah satu hal yang membuat angkutan umum tidak nyaman adalah tidak adanya integrasi antarmoda. Ini membuat masyarakat harus mengeluarkan upaya ekstra, baik secara fisik maupun materi, untuk sampai ke lokasi tujuan.
Perlahan, masyarakat harus didorong untuk beralih dari rasa nyaman membawa kendaraan pribadi menuju rasa nyaman menggunakan transportasi publik. Sebab, ini merupakan solusi satu-satunya untuk mengurangi kemacetan sekaligus mengembalikan langit biru Jakarta dan sekitarnya.
***
*) Oleh: Ahmad Jayadi, Pranata Humas Kementerian PUPR
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Rizal Dani |

