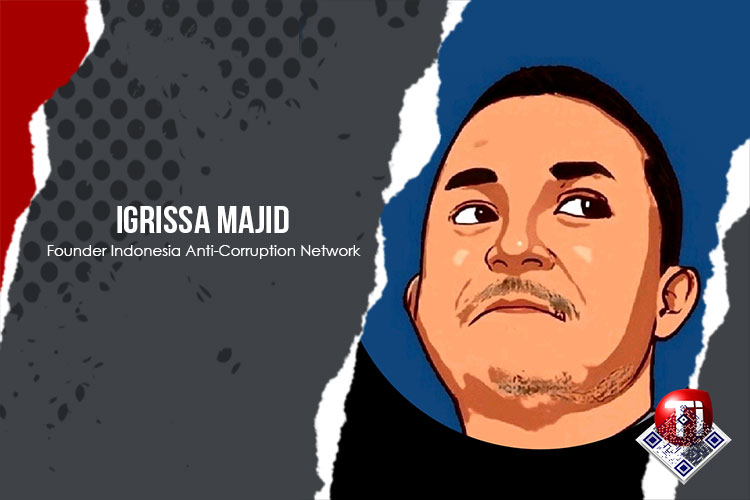
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Judul tulisan ini terinspirasi dari Philip I. Ackerman-Lieberman, yang berhasil menerbitkan buku bertajuk "The Business of Identity: Jews, Muslims, and Economic Life in Medieval Egypt." Liebermen sangat mendetail, mengulas dokumen hukum melalui referensi yang terdapat dalam dokumen Cairo Geniza untuk memahami pola kehidupan di pasar Islam.
Sisi lainnya, Ackerman-Liebermen mengurai kisah para pedagang Yahudi di Mesir menerapkan praktik perdagangan yang dipengaruhi langsung oleh hukum Yahudi untuk mewujudkan identitas mereka dalam konteks Islam abad pertengahan. Tapi saya tidak hendak pergi ke situ, dalam suasana Mesir di kala itu, tentunya.
Advertisement
Justru sekilas, saya hendak memotret Indonesia hari-hari ini, tentang pasar bebas politik yang di dalamnya terjadi bisnis identitas untuk meraih kemenangan dalam kontestasi politik. Baik agama maupun etnis.
Tentang kedua identitas itu, tegangan sentimentalnya belakangan meluluhlantakkan kondisi kehidupan demokrasi kita. Perpecahan karena faktor kubu-kubuan yang lokomotifnya langsung oleh panutannya masing-masing. Ya, mungkin berbeda jika kita mengikuti peta Mesir di abad pertengahan.
Kondisi Pasar Politik
Bahwasannya pasar politik merupakan proses monetisasi suara konstituen dengan sistem supply and demand (Mary Kaldor & Alex de Waal, 2020). Diatur secara sistematis agar dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara. Bahkan terjadi barter sistemik dalam pasar itu. Dalam suasana pasar politik Indonesia tercipta dalam dua kondisi, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.
Dalam suasana ini, produsen utama tentang identitas tidak lain hulunya bersumber dari tokoh-tokoh tertentu. Mereka menciptakan wadah untuk menampung orang sebanyak mungkin dengan kesamaan agama maupun suku. Tokoh-tokoh tersebut menjadi penjual atau subyek utama bagi pengikutnya. Layaknya para konstituen adalah barang konsumsi untuk memuaskan pelanggan.
Dalam fragmentasi agama, identitas ini kerap mengalahkan norma hukum. Agama menjadi piranti solidaritas sosial. Aktor-aktor yang mengatasnamakan agama telah mendoktrin bahwa kesalehan seorang pemimpin adalah syarat mutlak untuk menduduki jabatan publik yang melalui proses demokrasi prosedural.
Lain halnya dengan sisi etnis, bahwa unsur-unsur kesamaan dalam identitas etnis akan saling menopang untuk keberlanjutan sumber daya ke depan, karena ada basis kekerabatan.
Memang kasus sentimental agama dan etnis di Indonesia tidak lain karena keteledoran pemimpin yang terpilih. Tidak berupaya menyatukan setiap patron dari tiap-tiap kelompok baik agama maupun etnis dalam satu kerukunan yang murni.
Justru sentimen golongan yang disebut pribumi dan pendatang terbiarkan dan berdampak pada penyimpangan pasar politik. Banyak kasus misalnya, coretan Kantor Bupati di Halmahera Barat bertuliskan "Kantor ini Tabaru Punya"; spanduk bertuliskan "pribumi muslim" saat pelantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta, kasus Ahok di Jakarta, dan masih banyak kasus serupa lainnya.
Meskipun demikian, antara agama dan etnisitas sama-sama secara hierarki memiliki patron. Keduanya berada dalam satu lingkar komando untuk menaruh pilihan kepada kontestan tertentu. Afiliasi politik tiap-tiap patron sangat menentukan pilihan bagi pengikutnya. Mereka menguasai sebagian besar kekuatan konstituen tanpa memperhitungkan batasan ideal dalam demokrasi. Setiap individu memiliki hak tersendiri untuk menentukan pilihan.
Patron dari masing-masing identitas ini semuanya selaras untuk berkontribusi dalam pembentukan identitas agama maupun etnis. Tujuan politik mereka sesungguhnya adalah untuk mendapatkan akses terhadap kekuasaan hanya dengan memanfaatkan identitas agama maupun etnis.
Logika Dagang
Tidak ada proses barter gagasan dengan dukungan elektoral. Semua dikapitalisasi dengan kalkulus oportunistik yang bersifat individual. Tawar menawar secara matematis harus benar-benar diperhitungkan agar saling menguntungkan. Logika dagang bermain dalam arena ini.
Memang, kebiasaan politik transaksional tidak mudah dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kecukupan modal. Para ilmuwan politik, sosial, hukum, maupun pakar keilmuwan lainnya tidak mudah memusnahkan kebiasaan ini lewat paparan ilmiahnya.
Modal kapital ternyata jauh lebih kuat daripada modal intelektual. Kepongahan jauh lebih berkuasa daripada kekuatan rasionalitas. Mereka yang memiliki massa real justru semaunya memonoopoli harga suara para pengikut semaunya.
Identitas adalah modal dagang. Modal ini memang dapat berujung brutal, merusak sendi-sendi demokrasi, jika tidak ditata dengan baik dalam etalase politik. Logika dagang para patron dari identitas kelompok agama maupun etnisitas ini justru mengorbankan kelompoknya sendiri. Tawar menawar dalam bisnis identitas agama maupun etnis tidak menekankan tujuan bersama tiap-tiap individu dalam satu kelompok.
Kekuatan patron, menciptakan cara pikir baru dalam politik. Bahwa politisasi identitas adalah bentuk kewajaran dalam demokrasi. Ada relasi yang mengikat antara politik identitas dan kapitalisasi terhadap semua pengikut dalam satu kelompok identitas agama maupun etnis. Kritik Wendy Brown (1995), ilmuwan politik Amerika, ternyata benar.
Dalam kondisi berdemokrasi hari-hari ini, politik identitas mempunyai hubungan atau silsilah dengan kapitalisme. Indonesia sedang di fase ini, ketika para pemuka agama maupun kepala suku berjarak dekat dengan kapitalisme. Maka mereka memiliki hubungan bisnis jangka panjang bernama identitas.
Melampaui Identitas
Mungkin kita harus pergi berjelajah dalam ruang perpustakaan milik John Rawls. Setidaknya muncul hasil eksperimentasinya tentang "original position." Rawls telah mengaktualisasikan bahwa setiap individu itu serupa. Yang dimaksud Rawls entah serupa wajah, warna kulit, orientasi seksual atau etnis maupun agama.
Karena di sini, Rawls menekankan pada pelepasan semua identitas, maupun preferensi terhadap hal tertentu, agar dapat membuat suatu keputusan yang rasional dalam bernegara (Rawls, 1971).
Memang rasionalitas hanya dapat dicapai ketika kita tidak harus tunduk dan patuh pada orang secara pribadi maupun kelompok tertentu. Tidak menjadi hamba bagi manusia lainnya hanya karena jubah keagamaan maupun pernak-pernik kesukuan yang melekat dan menjadi simbol.
Rasionalitas akan menjadi "kuasa baru" dan mengakrabkan sistem kewarganegaraan satu sama lain, menunjukkan kepada kita tentang kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi. Mengembalikan hak tiap-tiap warga negara kepada posisi aslinya (original position) sebagai manusia yang merdeka, yang enggan masuk dalam ruang kotor bernama politik identitas.
Karena itulah, rasionalitas dapat menjadi instrumen untuk melompat jauh melampaui politik identitas. Sebab, menerima hasil dari transaksional identitas agama maupun etnis.
Secara tidak langsung telah menjadi spesies yang diproduksi oleh struktur yang menindas. Identitas agama maupun etnis memang sesuatu yang mulai melekat di tiap kelompok. Tapi identitas itu bukan diperdagangkan untuk kepentingan segelintir orang dalam satu kelompok.
***
*) Oles: Igrissa Majid (Founder Indonesia Anti-Corruption Network)
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |

